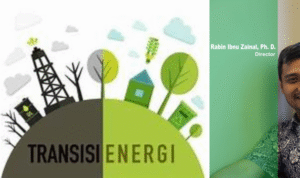Oleh: H. Albar Sentosa Subari
(Ketua Peduli Marga Batang Hari Sembilan)
Marshal
(Pemerhati Sosial dan Hukum Adat Indonesia)
Kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah memicu perdebatan yang melampaui ranah teknis pendidikan. Surat edaran yang melarang kegiatan study tour sekolah dengan alasan menghindari beban ekonomi bagi orang tua serta kurangnya kontribusi terhadap pembentukan karakter siswa, justru membuka babak baru dalam relasi kuasa di tingkat pemerintahan daerah.
Namun, yang menarik dari polemik ini bukan semata soal substansi larangan tersebut. Pro-kontra itu justru menyeruak karena penolakan keras datang bukan dari masyarakat, bukan pula dari pelaku pariwisata yang memang terdampak, tetapi justru dari sesama kepala daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat.
Enam kepala daerah, mulai dari Walikota Bandung hingga Bupati Sumedang, secara terbuka menyatakan tidak akan mengindahkan larangan gubernur.
Mereka memilih tetap memperbolehkan sekolah-sekolah di wilayahnya melakukan study tour, karena dinilai masih memberi manfaat dan merupakan bagian dari otonomi daerah masing-masing.
Inilah wajah dari realitas sistem pemerintahan pasca reformasi. Ketika Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada, maka mereka pun merasa memiliki legitimasi yang setara.
Padahal secara konstitusional, Gubernur juga memegang peran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, bukan sekadar kepala daerah biasa. Dalam praktiknya, fungsi ganda ini kerap menimbulkan ketegangan struktural maupun emosional.
Disharmoni antara level provinsi dan kabupaten/kota bukan hal baru. Undangan gubernur yang tidak dihadiri bupati atau walikota, misalnya, adalah cerminan betapa renggangnya relasi antar pemangku kepentingan ini. Rasa “sama-sama dipilih rakyat” sering kali menempatkan mereka dalam posisi kompetitif, bukan kolaboratif.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka potensi konflik kebijakan akan terus berulang. Satu sisi membuat kebijakan publik atas nama rakyat, sisi lain menolak dengan dalih otonomi yang juga sah menurut undang-undang. Maka, perlu kiranya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan fungsi pemerintahan daerah saat ini.
Salah satu gagasan yang patut dipertimbangkan adalah menjadikan gubernur semata sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, bukan sebagai kepala daerah provinsi. Dengan demikian, tidak perlu lagi pilkada gubernur, apalagi DPRD provinsi. Otonomi penuh cukup berada di tingkat kabupaten dan kota, sementara gubernur hanya bertugas mengkoordinasikan dan menjalankan fungsi administratif pusat.
Dengan mekanisme seperti itu, gubernur akan lebih dihormati sebagai pejabat negara, bukan sekadar pesaing politik kepala daerah lainnya. Pengangkatan dan pelantikan kepala daerah tetap melibatkan gubernur, namun tanpa tumpang tindih kewenangan yang selama ini memicu ego sektoral dan disharmoni birokrasi.
Perseteruan antar kepala daerah seperti di Jawa Barat ini seharusnya menjadi alarm bagi para pembuat kebijakan nasional. Jangan sampai semangat otonomi daerah yang semula ingin mendekatkan pelayanan publik ke rakyat, justru menjauhkan para pemimpin daerah dari kerja sama yang harmonis.
Sudah saatnya DPR RI dan Pemerintah pusat mengevaluasi ulang sistem pemerintahan daerah dalam kerangka UUD 1945 dan semangat Pancasila. Indonesia membutuhkan sistem yang tak hanya demokratis, tetapi juga efektif dan bersinergi untuk mencapai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat.